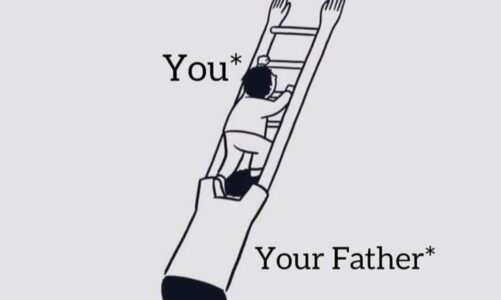Oleh: Biera
Saya ingat ketika melintas di jembatan di daerah Z. Rumah Suginur, teman dulu di pabrik kerupuk, tak jauh dari jembatan ini. Sekitar sepuluh tahun lalu ketika masih satu pabrik, saya pernah berkunjung ke rumahnya.
Sebenarnya sama sekali tak membayangkan untuk membelokkan motor saya ke rumah kawan lama itu. Tetapi barangkali sudah takdir.
Saya tengah mengirim paket ke daerah B. Hampir tiga bulan ini saya bekerja sebagai pengirim paket. Setiap hari pula hidup saya banyak dihabiskan di jalanan. Untuk sementara, pekerjaan ini lebih baik dari sebelumnya. Tetapi ke depan, tak tahu lagi.
“Syukuri saja mas.. ” ujar istri saya beberapa waktu lalu.
Banyak bangunan baru di kiri kanan jalan menuju rumah Suginur. Dulu kawasan ini terbilang sepi. Saya beberapa kali berputar-putar. Hingga menyerah. Lalu mencari bantuan warga sekitar.
Ternyata Suginur kini menempati rumah istrinya. Rumahnya dulu dijual sepeninggal kedua orangtuanya.
Saya tiba di rumah yang dimaksud. Seorang lelaki berkumis lebat menghampiri saya. Baru setelah dua langkah kaki, saya mengenalinya dengan baik.
“Suginur??”
“Wibowo, kamukah itu hey teman??”
Lalu ia memeluk saya. Saya kaget bukan main. Masih saja dia seperti dulu. Waktu pamitan dari pabrik, dia juga memeluk saya. Tetapi harus saya akui, dia teman yang paling mengesankan.
Kami berjalan menuju rumahnya. Kami bercakap-cakap di beranda.
Tak berselang lama, sebuah suara memanggilnya dari dalam rumah.
“Pak. Bapak. Aku mau pipis..”
Sontak Suginur berdiri. Ia mengajak saya masuk ke ruang tamu.
Betapa terkejut saya ketika melihat kondisi anak laki-laki – saya pikir itu anak Suginur – yang berbaring di kasur depan televisi.
Suginur mengangkat tubuh anak itu. Sementara saya duduk di kursi. Melihat foto-foto yang terpajang di sana. Foto perkawinan. Foto anak lelaki itu.
“Ini diminum Wo..” ujarnya membuat saya kaget.
Seperti bisa membaca pikiran saya.
“Itu Iman Wo. Anak pertama saya. Usianya 18 tahun. Hey, sudah berapa istrimu, eh anakmu Wo..” katanya sembari tersenyum.
“Masih satu Nur. Istri juga masih satu.” ucap saya sambil tersenyum.
Saya penasaran. Tetapi saya menunggu. Akhirnya, Suginur cerita juga.
“Iman itu lumpuh Wo. Lihat kaki, tangan, dan punggungnya itu. Mengecil. Dulu ketika usia tujuh tahun, demam. Setelahnya ketika jalan sering ambruk. Kupikir waktu itu tidak seperti itu.” ia menghembuskan napas.
Saya melihat semacam duka dalam kelopak matanya.
“Terpaksa berhenti sekolah. Mau gimana lagi. Saya dan istri sudah ikhlas.”
“Lalu yang kecil itu?” saya menunjuk foto di dinding.
“Itu Amin. Adiknya Iman. Kami berharap dia bisa tumbuh normal seperti ornag tuanya. Tetapi ketika usia 5 tahun, hal serupa yang terjadi pada Iman, terjadi pula pada Amin. Keduanya lumpuh.”
Saya tercekat. Ternyata masalah yang menimpa saya tak ada apa-apanya dibanding cobaan yang menimpa Suginur.
“Ikhtiar terus kami lakukan Wo. Keajaiban pasti tiba. Bahkan si Iman ini tiap satu pekan sekali harus ke dokter. Dia ada gangguan pencernaan. Tidak bisa buang air besar. Jadi dibantu sama dokter.”
Dari luar, suara seorang perempuan tengah bercanda dengan suara anak laki-laki.
“Bu, ini Wibowo. Yang dulu sering tak ceritain itu lo..” ujarnya mengenalkan saya.
Ia tersenyum ramah. Lalu menyuruh anak di kursi roda itu untuk bersalaman dengan saya. Inilah mungkin si Amin itu. Kondisinya sama dengan kakaknya.
Setelah lama menukar kabar, saya berpamitan dengan Suginur. Di dompet saya ada uang 300 ribu. Uang yang saya kumpulkan untuk membelikan istri saya kalung. Rencananya akan saya berikan di hari ulang tahun pernikahan kami. Empat bulan lagi.
Suginur mati-matian menolak uang yang saya berikan pada anaknya. Tetapi saya juga mati-matian meyakinkan bahwa ini bukan belas kasihan.
“Nur, ini untuk mereka. Mereka juga tak anggap anak-anak saya juga Nur. Ini bukan belas kasihan. Bukan. Saya sudah menganggapmu saudara. Bukankah begitu?” ucap saya.
Suginur lagi-lagi seperti sinetron. Memeluk saya. Saya kaget lagi.
“Yang sabar. Yang kuat.” begitu saya bisikkan di telinga Suginur. Tetapi lebih tepat jika pesan itu untuk saya sendiri. Yang selama ini selalu merasa hidup saya selalu tidak beruntung. Selalu sial. []
26/1/2020
Menghitung sepi seusai hujan
*Penulis kini tengah menggandrungi Anton Chekov
Sumber gambar: https://pin.it/2lkJwjX
574 total views, 1 views today