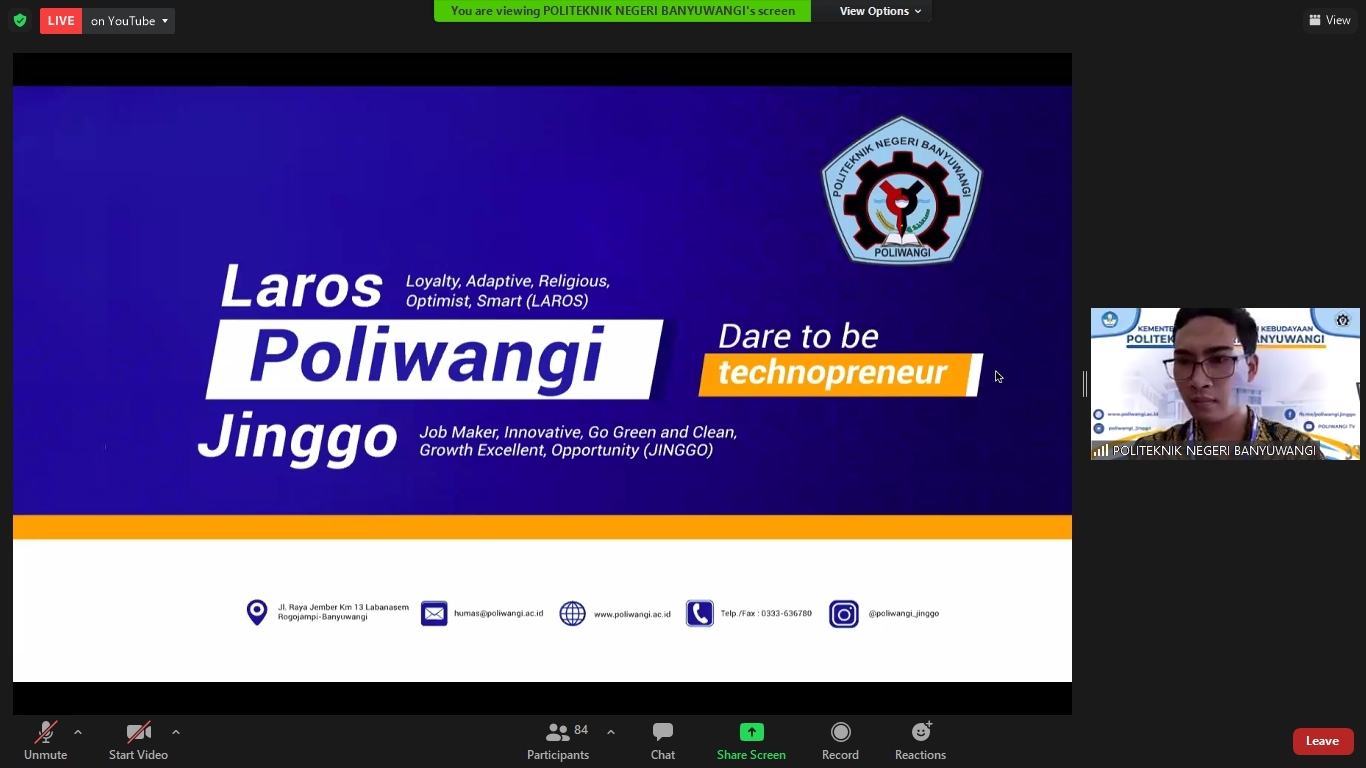Oleh: Nailah Rahmah
Saya lahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Usia saya terpaut jauh sekali dengan ketiga kakak saya. 11-18 tahun jaraknya. Karena itu, kini hanya saya yang masih duduk di bangku sekolah di keluarga saya.
Ungkapan ”Anak terakhir mah pasti dimanja!”
Seringkali terdengar oleh saya. Saat itu, saya hanya mengiyakan saja. Tetapi, faktanya tidak semanis itu.
Sejak saya duduk di bangku sekolah dasar, saya hidup dengan bayang-bayang Kakak.
”Kakak kamu dulu selalu peringkat satu!”
”Kakakmu dapet beasiswa lho!”
”Kakakmu kuliah di luar negeri, nanti kamu juga, ya!”
Ucapan-ucapan seperti itu sudah sering saya dengar sejak SD. Entah sengaja atau tidak, orangtua saya secara tidak langsung mendorong saya untuk minimal bisa menyamai pencapaian ketiga kakak saya. Dan saya pun dengan banyak ambisi, berusaha memenuhinya.
Tapi ternyata tidak berjalan semulus yang saya kira. Saya ternyata tidak sepintar Kakak. Tidak seberbakat Kakak. Dan tidak se-lainya dibanding mereka. Saya bahkan tidak tahu apa yang ingin saya lakukan kedepanya. Hal ini cukup menekan saya. Satu per satu 100 goals yang saya catat di buku harian, saya coret. Hanya menyisakan beberapa yang masuk akal seperti ”makan bakso terenak di Surabaya” atau ”lengkapin series 5 sekawan” hehe.
Memasuki tahun kedua memakai seragam abu-abu putih, tandanya saya harus mulai menentukan jalan masa depan saya. Kalau boleh lebay sedikit, ibaratnya seperti sedang mencari cahaya saat tersesat di gua yang gelap. Cahaya itu yang nantinya saya harap bisa mengalahkan bayang-bayang yang selama ini menghantui saya. Bayang-bayang kegagalan. Bayang-bayang kekalahan.
Namun, entah mengapa saya merasa seperti berlomba. Semua orang terasa berlari kencang. Padahal, saya ingin berjalan saja. Padahal, saya tidak mau ikut berlomba. Tetapi tiba-tiba orang-orang di sekitar saya sudah melangkah jauh sekali. Saya terus merasa ketinggalan. Saya terus terengah-engah. Dan saya terus merasa kalah.
Sampai saya membaca buku milik Kakak saya. Filosofi Teras judulnya. Tidak semua isi buku itu saya pahami. Tetapi beberapa poin dari buku itu menyadarkan saya. Kalau saya tidak perlu berekspektasi lebih. Saya tidak perlu melihat pencapaian Kakak saya untuk memvalidasi berhasil atau tidaknya saya. Saya tidak perlu mematahkan pencapaian Kakak saya untuk diakui orangtua saya. Saya cukup berusaha sesuai dengan kadar yang saya punya.
Saya juga mulai merasionalkan mimpi-mimpi saya. Saya cukup dengan selalu merasa cukup agar tidak merasa kalah. Kalimat demi kalimat yang saya baca menampar saya. Menyadarkan untuk mulai membenahi mindset saya. Menghentikan saya dari lomba lari yang tak ada garis finish nya ini.
Mungkin, entah sampai kapan, ”silau”nya pencapaian Kakak akan tetap membayangi saya. Tapi dengan mindset yang berbeda, bayangan itu sudah tidak menghantui saya. Dan semoga, sampai kelak pun saya tidak pernah merasa kalah lagi.
~Penulis merupakan salah satu siswi di SMA Khadijah yang duduk di bangku kelas 11 mipa 2